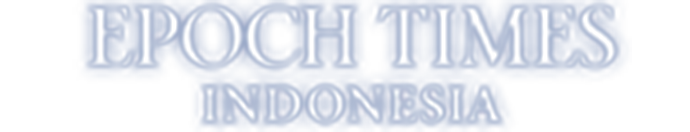ISWAHYUDI
Naskah kuno adalah harta karun bagi generasi sekarang dan mendatang yang tak ternilai. Ada banyak pesan moral, prinsip-prinsip kuno dan kearifan yang tak lekang oleh waktu.
Saat globalisasi merupakan jalan buntu dan bentuk baru dari penjajahan itu sendiri, membaca kembali naskah kuno sering memberikan inspirasi tentang bagaimana arah peradaban ini seharusnya ditempuh dan tidak menutup kemungkinan ini bagian dari solusi.
Dalam sejarah kerajaan Ngayogyakarta pernah terjadi sebuah peris- tiwa yang disebut sebagai bencana budaya. Dikutip dari Indonesia. go.id (11/03/2019) bahwa Pada 20 Juni 1812, pasukan Inggris-Benggala menyerbu Keraton Yogyakarta. Peristiwa itu terkenal sebagai Geger Spehi (Spoy) yang merupakan catatan hitam sejarah kolonial Inggris. Peter Carey mencatat dalam peristiwa itu 23 orang pasukan Inggris mati dan 78 lainnya terluka, sementara korban ribuan di pihak keraton.
Yang lebih memilukan dari semua itu adalah perilaku pasukan kolonial Inggris yang menjarah kekayan dan benda- benda budaya yang dianggap berharga termasuk naskah kuno. Majalah Historia menulis, peti-peti kayu jati dan lemari dari keraton hilir mudik diangkut dengan menggunakan gerobak menuju Benteng Vederbergh dan Kepatihan selama empat hari lamanya.
Jika dijumlahkan nilainya melebihi 120 juta dolar. Jarahan itu kemudian dibagikan kepada seluruh pasukan berdasarkan kepangkatan. Sedangkan naskah-naskah dari perpustakaan keraton dan arsip-arsip dari sekretariat atau Gedhong Pacarikan dibawa ke Kepatihan tempat British Residency dan membaginya kepada Raffles, Crawfurd dan Mackenzie.
Hingga saat ini belum ada gambaran yang bisa memperkirakan berapa banyak naskah-naskah yang dijarah. Dalam pidato pembukaan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengutip penelitian sejarawan UGM Djoko Suryo yang memperkirakan sejumlah 7.000 naskah yang hilang dari keraton.
Semenjak saat itu terjadi kemunduran yang luar biasa dalam tradisi tulis-menulis di Keraton Yogyakarta karena yang tersisa di dalam keraton hanya tinggal 3 (tiga) peninggalan, yakni Serat Suryorojo (1774), Serat Arjuna Wiwaha (1778), dan Kanjeng Kyai Qur’an.
Keserakahan Refless dan pasukannya telah membuat bencana kebudayaan bagi keraton Yogjakarta khususnya dan seluruh nusantara. Namun Faktanya keinginan dan nafsu serakah yang diperlihatkan oleh Raffles pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa kecuali kerusakan di berbagai pihak.
Salah satu akibat keserakahan Raffles adalah apa yang terkenal sebagai Kutukan Prasasti Minto. Prasasti tersebut berada di halaman rumah bekas kediaman Lord Minto, penguasa pasukan Kolonial Inggris urusan Hindia Belanda.
Prasasti ini berasal dari Desa Sangguran di Malang, adalah sebuah prasasti peresmian daerah kuno di Malang dengan beberapa ayat di prasasti yang memberikan kutukan kepada siapapun yang melanggar berbagai aturan yang ada di dalam prasasti itu akan binasa.
Lord Minto dipecat dengan alasan tidak jelas untuk kemudian mati tanpa sempat melihat prasasti di halaman rumahnya. Demikian juga dengan Raffles yang juga mengalami pemecatan dalam karier tentaranya dan mati akibat sakit sesudahnya. Tak kurang pula bupati Ranggalawe yang menghadiahkan prasasti itu kepada Raffles, hingga saat ini namanya tidak banyak dikenal di daerah asalnya dan makamnya pun tidak diketahui di mana rimbanya.
Sejarah singkat penggubah Serat Suryorojo
Dari penjarahan tersebut hanya tinggal tiga naskah kuno yang tersisa salah satunya adalah serat Suryorojo, Karya Sri Sultan Hemangkubuwono II (RM Sindoro), yang banyak peneliti barat menyimpulkan merupakan karya fiksi. Namun seorang Filolog KRT Manu J Widyaseputra meyakini bahwa itu bukan fiksi melainkan sejarah intelektual yang dikemas dalam bentuk mitologi sebagai codex-codex rahasia yang harus diungkap oleh generasi berikutnya.
Serat Suryorojo ini ditulis oleh RM Sindoro pada 1774 ketika masih berumur 24 tahun. Sebagai seorang putra raja ternyata, beliau tidak lahir di keraton. Lahir di lereng Gunung Sindoro pada 7 Maret 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hameng- kubuwono I, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Kadipaten, di wilayah pe- ngungsian akibat perang melawan VOC. Situasi tersebut kelak membentuk karakter yang keras pada diri Sri Sultan Hamengkubuwono II.
Pasca perjanjian Giyanti, RM. Sundoro mulai tinggal di dalam keraton dengan status putera raja. Pada 1758, ketika RM Sundoro dikhitan, beliau diangkat menjadi putra mahkota, mengantikan kakaknya Raden Mas Ento yang meninggal sepulang dari perjalanan ke Borobudur. RM Sundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton dan berupaya melindungi Keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC.
Beliau berupaya menggagalkan pembangunan Benteng Rustenburg dengan membangun tembok B mengelilingi alun-alun utara dan selatan dan menyiapkan 13 meriam menghadap ke arah ben- teng VOC.
HB II terkenal dengan sikap anti penjajahan baik terhadap VOC, Kerajaan Belanda, dan kolonial Inggris. Banyak peristiwa besar yang dialami selama menjadi Sultan mulai bangkrutnya VOC, pendudukan kerajaan Belanda di bawah Deandels, Serangan Raffles terhadap Keraton Yogyakarta pada 20 Juni 1812, diasingkan dua kali, naik tahta 3 kali, dan perang Jawa yang merepotkan Belanda oleh Pangeran Diponegoro. Dan tutup usia pada 3 Januari 1828 dimakamkan di Kota Gede.
Karya-karya monumental di bidang sastra antar lain Babad Ni- tik Ngayogya, Babad Mangkubumi, Serat Baron Sekender, Serat Suryorojo (yang jadi pusaka bagi Keraton) dan menggubah lakon wayang kulit berjudul Jayapu- saka yang tokoh utamanya adalah Bima yang merepresentasikan watak jujur, keras dan tegas dari Sri Sultan Hamengkubuwono II.
Pesan kepemimpinan ‘Serat Suryorojo yang dianggap fiksi’
Menurut Filolog KRT Manu J Widyseputra bahwa Serat Suryorojo ditulis untuk memberikan pedoman bagi raja-raja Yogjakarta di mana sebelum serat ini ditulis, Keraton Yogjakarta berpedoman pada 4 Serat yaitu Serat Iskandar Zulkarnain, Serat Yusuf, Serat Suluk Garwa Kencono, Dan Suluk Usulbiyah. Ternyata RM Sindoro memilih menggubah teks yang baru yang akan menjadi pedoman bagi raja-raja di Yogjakarta yaitu Serat Suryorojo. Namun banyak peneliti menganggap ini sebagai karya fiksi.
Berdasarkan penelitian filologis ternyata serat ini mempunyai dasar yaitu 5 naskah yaitu Serat Tajussalatin Jawi, Serat Bustanus Salatin Jawi, Tuhfah Annhafis Jawi, Serat Tapal Adam, dan Serat Makuto Rojo. Untuk menguak pesan-pesan tersembunyi tersebut Filolog KRT Manu tidak bisa menggunakan kamus bahasa Jawa pada umumnya, melainkan harus menggunakan kamus khusus yaitu Kerto Boso yang pada waktu itu sudah tidak ada di keraton.
Namun ia mendapat warisan naskah dari Eyang Ageng Projodiningrat dan menemukan kamus Kertoboso yang ia cari. Ia baru tahu bahwa ternyata bahasa Jawa Ngayogjokarto itu sulit sekali. Karena satu kata sering mempunyai seratus arti.
Semenjak saat itu Filolog Manu meneliti kata per kata dari naskah Suryorojo itu yang keseluruhannya ada 2 jilid dengan 1000 lebih halaman. Dari hasil penelitian ini dia menemukan banyak hal yang berharga salah satunya prinsip-prinsip kemimpinan raja yang ditulis oleh RM Sinduro.
Secara bahasa (nirukta) Suryorojo berasal dari kata Suryo dan Rojo. ‘Suryo’ berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti mengalir dengan lembut atau berjalan dengan lembut. Ternyata benda yang mengalir atau berjalan dengan lembut adalah matahari.
Sebagaimana perjalanan matahari selama 24 jam berjalan atau mengalir dengan sangat lembut. Tidak pernah lelah dan jemu untuk menghidupi alam semesta. Yang dihidupkan oleh matahari tidak hanya bumi tapi juga planet-planet yang lain.
Semua kehidupan tergantung pada matahari. Selanjutnya kata ‘Rojo’ berasal dari kata Raj yang artinya yang memerintah. Sehingga kalau dua kata itu digabung berarti matahari sebagai raja.
Menurut KRT Manu dari sudut pandang kosmologi dan teologi bahwa raja itu selalu diumpamakan sebagai surya (matahari).Matahari itu didudukkan dalam konteks kosmologi sebagai pradista yang berarti penyangga, dasar atau landasan.
Jadi surya itu menjadi penyangga bumi ini. Menyangga keberlangsungan kehidupan di bumi ini. Kalau bumi ini tanpa ada surya. Tidak akan bisa berputar. Andaikata Surya ini mogok satu menit, bumi ini bisa hancur. Maka ia menjadi raja yang mengatur kehidupan dalam bumi ini.
Serat Suryo Rojo ini berisi aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengatur bumi ini (wilayah kekuasaan sang raja). Kalau raja memerintah dari perspektif kosmologi akan menjadi cakrawartin yang berarti menyelimuti bumi yang menjadi kekuasaannya. Pada posisi ini raja mempunyai dua fungsi.
Pertama, sebagai bhumipati yang berarti suami dari bumi yang dikuasai. Jadi seorang raja harus menjadi suami dari bumi yang harus melindungi istrinya. Yang berarti menjaga kelestarian ekologi dari bumi yang dikuasainya seperti tanah, laut, hutan, sungai, dan makhluk- makluk yang lain.
Pada titik ini seorang raja atau pemimpin harus punya pengetahuan dan kesadaran terhadap ekologinya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena bumi yang memberi kehidupan langsung pada raja maupun rakyatnya.
Mengingat Yogjakarta adalah bagian dari Mataram Kuno yang secara bahasa kata Mataram berasal dari kata mata yang berarti ibu dan aram yang berarti hiburan, atau persembahan untuk ibu. Secara bukti arkeologis banyak ditemukan arca durga di Yogjakarta. Durga dikenal sebagai dewi pertanian yang memberikan makan pada semua yang tinggal di wilayah ini.
Menurut catatan sejarah bahwa Mataram pernah menjadi pengekspor beras hampir di seluruh Asia. Tapi sayang sekali sekarang tinggal kenangan saja.
Kedua, sebagai Prajapati yang berarti suami rakyat. Yang punya tanggung jawab melindungi rakyatnya. Jadi raja itu tidak sekedar memerintah lalu menyuruh-nyuruh. Dia berkewajian untuk melindungi rakyatnya. Yang dimaksud praja di situ bukan hanya manusianya tapi binatang baik buas maupun peliharaan. Semua harus dilindungi oleh raja ini.
Dua konsep kepemimpinan ala Serat Surya Raja ini sebenarnya sangat relevan bagi Indonesia yang sering menghadapi bencana ekologis akibat salah mengelola bumi. Contoh kasus adalah paradigma tentang hutan.
Para penguasa sekarang kebanyakan memandang hutan sebagai komoditi ekonomi saja sehingga terjadi deforestasi di mana-mana yang berunjung pada bencana ekologi. Ini kontras dengan para raja dulu memandang hutan sebagai pusat peradaban, di mana di hutan ada banyak asrama sebagai agen perubahan.
Mungkin kalau paradigma hutan sebagai pusat peradaban masih dimiliki Indonesia saat ini, ketika deferestasi terjadi masif di seluruh dunia, maka pastinya Indonesia menjadi tujuan wisata ekologis nomer satu di dunia yang akan memberikan manfaat ekonomi. Tapi kini sekedar pengandaiaan belaka, karena penyesalan pasti datang belakangan. Dari sini, bisa diambil pelajaran, bahwa ajaran leluhur bahwa hutan sebagai pusat peradaban sangat relevan sekali.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah merupakan pendapat penulis pribadi dan belum tentu mencerminkan pandangan The Epoch Times