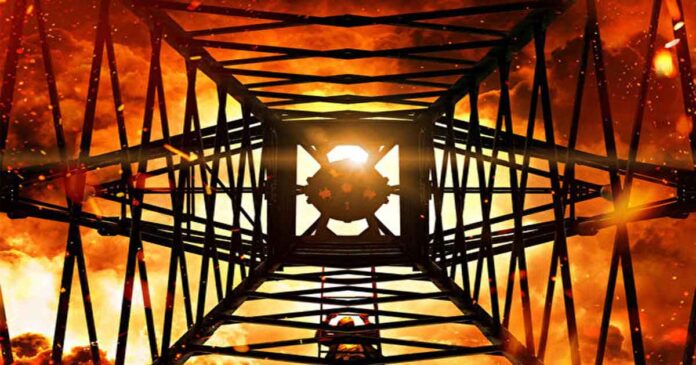Li Yongchun
Pada saat film “Oppenheimer” ditayangkan, penulis termasuk yang pertama menyerbu gedung bioskop untuk menyaksikannya, dan menikmati durasi film selama 3 jam yang menyenangkan. Sebelumnya sudah banyak orang membahas tentang film ini di internet, dan didapat pandangan yang seragam bahwa agar bisa menikmati film ini sebaiknya harus dilakukan sejumlah pekerjaan rumah yakni, membaca sejumlah buku, dan menambah beberapa pengetahuan terkait latar belakangnya.
Memang, setelah menyaksikan film ini penulis merasa sangat menikmatinya, dan merasakan telah memperoleh banyak manfaat. Sutradara dan para penulis skenario pasti telah melakukan banyak upaya dan mencerna banyak sekali materi dari berbagai aspek, serta memeras otak untuk menghasilkan sebuah film epik yang makroskopis, menyeluruh, namun sangat detil.
Penulis seorang diri menguasai salah satu pojok gelap di dalam gedung bioskop, serta seiring dengan bergulirnya alur cerita selama tiga jam itu, segala buku terkait dan pengalaman individu yang pernah penulis baca selama bertahun-tahun yang ada dalam ingatan saya mengalir keluar ibarat air, dan terkumpul menjadi perairan yang luas dengan
Oppenheimer sebagai pusatnya; film ini juga ibarat begitu banyak serat-serat teratai yang rumit namun saling terhubung menyatukan serpihan yang berserakan ke tempat yang semestinya, serta merampungkan suatu puzzle besar yang berwarna warni dan begitu agung.

Untuk bisa memahami film ini, sangat mungkin pembaca harus memiliki kemampuan pemahaman tertentu terhadap beberapa topik berikut ini:
1. Mayoritas peran dalam film ini ada kaitannya dengan bidang sejarah perkembangan ilmu fisika modern, khususnya fisika atom dan mekanika kuantum, oleh sebab itu jika tak mampu memahami kontribusi, dampak, dan interaksi di antara mereka dalam sejarah perkembangan ilmu fisika modern, maka akan sangat sulit memahami sejumlah alur cerita yang krusial dalam film ini.
2. Hubungan sebab akibat dalam Proyek Manhattan, serta dampaknya terhadap PD-II dan program ilmiah pemerintah AS di kemudian hari.
Ini adalah suatu proyek raksasa AS selama 3 tahun (1942-1945) dengan mengumpulkan sumber daya negara dan orang-orang yang terbaik kala itu, untuk dalam satu gerakan, menciptakan suatu senjata pamungkas yang mampu menghancurkan peradaban manusia, karena ada pemikiran yang kebetulan (dikarenakan Albert Einstein khawatir Nazi Jerman akan lebih dulu mengembangkan senjata nuklir, maka ia menulis surat kepada Presiden AS Franklin D. Roosevelt), namun malah mendekati inti dari peradaban umat manusia dan takdir pamungkasnya.
3. Tren haluan kiri dari kalangan cendekiawan dan McCarthyisme di AS pada era 1950-an.
Ada yang mengatakan gelombang merah komunisme mencapai puncaknya pasca PD-II (1945), maksudnya kubu komunis yang berpusat pada Uni Soviet telah menguasai sekitar setengah dari peta dunia. Paradoksalnya adalah beberapa tahun semasa PD-II, berkat AS sebagai pusat super industri militer dunia yang terus menerus memberikan bantuan bagi sekutunya di masa PD-II yakni Uni Soviet, yang justru hal itu telah membesarkan peta dunia komunisme. Menunggu sampai para tokoh dunia politik AS tersadarkan, serta merasakan adanya ancaman dan invasi pemerintahan totaliter komunisme terhadap dunia demokrasi bebas, barulah berubah seratus delapan puluh derajat, dengan berusaha keras melawan kelompok komunis yang dipimpin Uni Soviet. Akan tetapi telah secara berlebihan membersihkan kaum liberalisme yang berpikiran sayap kiri di dalam negeri AS, dan hal ini telah menimbulkan efek McCarthyisme yang menyeramkan yang dibarengi dengan karakteristik kuat ibaratnya perburuan para penyihir di abad pertengahan Eropa.
Oleh sebab itu, makna dan ambisi dari film ini adalah luar biasa besar, selain itu juga telah berhasil mencapai targetnya. Penulis merasakan, film “Oppenheimer” ini juga telah memecahkan rekor teraneh dalam sejarah perfilman, yaitu: “Setiap orang sangat menikmati film itu, namun kedalaman konten yang diperoleh setiap orang sebenarnya adalah sangat berbeda.”
Setelah film tersebut usai, serta mengiringi sekelompok penonton yang meninggalkan bioskop tanpa bersuara, saya sebenarnya ingin sekali menghadang mereka dan dengan lantang menceritakan konten yang saya dapatkan setelah menyaksikan film itu, termasuk cerita yang telah disampaikan, juga bagian dari cerita yang belum sempat tersampaikan dalam film. Padahal “cerita-cerita” itu berasal dari buku-buku sana-sini yang pernah saya baca secara acak selama empat dasawarsa terakhir.

Empat dasawarsa lalu tatkala penulis masih di bangku kuliah, sudah membaca buku berjudul “Surely You’re Joking, Mr. Feynman!” karya peraih hadiah Nobel Fisika Richard Feynman. Ia dijuluki sebagai “bocah nakal abadi dunia ilmiah”, ini adalah sebuah buku bersifat kenangan dengan cita rasa melimpah dan hidup, yang menceritakan perjalanan hidupnya dari kecil hingga dewasa, tentunya juga meliputi proses dirinya perlahan mengenal mekanika kuantum saat menempuh studi di MIT, Princeton, dan Cornell, termasuk juga semua pernak pernik yang dialaminya selama terlibat dalam Proyek Manhattan. Lewat buku semacam ini, penulis untuk pertama kalinya mengetahui tentang Proyek Manhattan yang dijalankan oleh AS semasa PD-II, Feynman yang waktu itu masih muda belia di usianya yang masih 20-an tahun telah terpilih oleh Oppenheimer untuk bergabung di tim fisika teori dalam proyek tersebut, guna membantu pekerjaan kalkulasi fisika dalam jumlah besar.
Di dalam buku itu cukup besar porsi yang menjelaskan bagaimana Faynman muda mengerjai para personil militer yang serius dan kaku, termasuk sang pemrakarsa Proyek Manhattan sejati yakni Mayjend Leslie Richard Groves Jr. dari Korps Zeni Angkatan Darat AS, yang diperankan oleh aktor terkenal Hollywood Matt Damon. Film itu telah menambal kurangnya gambaran citra buku empat puluh tahun silam itu. Dalam film “Oppenheimer”, frekuensi munculnya Feynman tidak banyak, misalnya pada saat pertama kali dilakukan uji coba ledakan nuklir si pemuda berbadan tinggi yang tidak mau mengenakan kacamata pelindung, dan hanya duduk seenaknya sendiri di dalam jeep dengan bermain drum.
Akan tetapi, yang benar-benar menyentuh pemahaman saya terhadap Oppenheimer, sebenarnya adalah sebuah buku yang tak sengaja saya temukan saat masih muda yang berjudul “Disturbing the Universe”, karya Freeman Dyson, seorang Inggris yang juga seorang ahli matematika dan fisika yang jenius. Di masa PD-II saat masih duduk di bangku kuliah ia telah direkrut untuk mengabdi di Angkatan Udara Inggris, pada 1947 usai PD-II ia kuliah di Cornell University di AS, serta telah mengenal Faynman yang lima tahun lebih tua darinya, dan mereka pun bersahabat.
Dalam buku itu Dyson secara rinci menceritakan bagaimana ia mengenal si jenius bernama Faynman yang hebat itu di Cornell University, dan ikut belajar mekanika kuantum terbaru dan metode perhitungan berpola gambar dengannya. Dengan sentuhan tulisannya yang begitu halus dan hidup ia menggambarkan di dalam jurusan ilmu fisika di Cornell University pada saat itu, termasuk Faynman beserta banyak akademisi yang pernah terlibat dalam Proyek Manhattan, bagaimana mereka menghadapi peristiwa penting yang terjadi pada Oppenheimer; termasuk betapa ia sangat menyesal telah menyelenggarakan penelitian bom atom, dan ia merasa kedua tangannya berlumuran darah; serta bagaimana di bawah pemeriksaan dan penindasan oleh kaum McCathyisme ia terpaksa menghentikan segala penelitian terkait energi atom.
Dalam buku ini Dyson juga menyebutkan, bagaimana ia berwisata dengan berkendara bersama Faynman, dari Cornell University mengemudikan mobil mengelilingi Amerika satu putaran besar, yang akhirnya sampai di Princeton University, untuk menemui Oppenheimer yang kala itu menjabat sebagai Direktur The Institute for Advanced Study. Dalam buku itu ia juga beberapa kali menyebutkan kontak, interaksi, dan observasinya pada Oppenheimer di Princeton University, dengan sangat hidup dan secara tiga dimensi telah menciptakan sosok Oppenheimer yang agung, rumit, sangat mendalam, dan multi aspek. Sekarang jika dipikir-pikir lagi, kemampuan menulis Dyson dapat dikatakan setara dengan kemampuan interpretasi film oleh sutradara Christopher Edward Nolan.
Dengan metode observasi jarak dekat, Dyson dengan persentuhan, pengamatan, dan pemahamannya dari tangan pertama, telah menginterpretasikan bagaimana para ilmuwan dalam Proyek Manhattan menyikapi kegalauan, kekusutan, dan pergumulan di hati mereka di kemudian hari. Dalam kehidupan setelahnya, seperti halnya sebagian ilmuwan dalam Proyek Manhattan itu, di kemudian hari Dyson juga ikut ambil bagian dalam aksi menentang pengembangan nuklir dalam rangka upayanya mewujudkan perdamaian dunia.
Buku ketiga yang berkaitan dengan film “Oppenheimer” adalah sebuah buku yang saya temukan secara tidak sengaja, yakni sebuah artikel memoar mengenai seorang fisikawan keturunan Italia bernama Enrico Fermi. Pastinya Fermi adalah seorang fisikawan besar dalam ilmu fisika modern dan ilmu atom, selain pernah meraih hadiah Nobel fisika, ia juga seorang pelopor dan pendiri sejumlah penelitian baru fisika modern. Yang lebih penting lagi adalah, penelitiannya menggabungkan teori dan eksperimen, berikut prestasinya yang paling terkenal adalah telah mewujudkan reaksi berantai pembelahan inti atom yang pertama kalinya bagi umat manusia di sebuah pabrik di University of Chicago, dan ia merupakan salah seorang perancang serta pencipta bom atom, sehingga dijuluki “bapak energi atom”. Dalam film “Oppenheimer”, kemunculan Fermi tidak sedikit, dan aktor yang memerankannya juga sangat mirip dengan Fermi, perawakannya pendek kecil, ada sedikit botak, dan langsung bisa dikenali ketika ia muncul.
Fermi sendiri bukan orang Yahudi, tetapi istrinya adalah orang Yahudi, oleh sebab itu mereka juga telah meninggalkan Italia dan hijrah ke Amerika pada saat tren NAZI dan fasisme memuncak di era 1930-1940-an. Saya menemukan buku dalam bahasa Inggris ini, yang sebenarnya merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh murid-muridnya untuk memperingati dan mengenangnya. Dalam buku ini, juga disinggung tentang seorang sosok penting lainnya dalam film “Oppenheimer” yakni Edward Teller, ia adalah ahli fisika teori keturunan Yahudi yang dilahirkan di Hungaria, yang kemudian dijuluki sebagai “bapak bom hidrogen”. Karakter Teller dalam film “Oppenheimer” agak negatif, aktor yang memerankannya juga sangat mirip dengan Teller dalam fotonya, berbadan tinggi besar, bermata lebar, beralis tebal, sosok yang dipenuhi dengan depresi, konflik, dan kegelisahan.
Dalam film dan dunia nyata, sosok Teller penuh dengan kontroversi, penyebab utamanya ialah ia sangat mendukung AS yang seharusnya mengembangkan bom hidrogen dengan lebih kuat lagi, dengan kekuatan militer men-deteran (menakuti) negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan lain-lainnya. Mungkin ini ada kaitannya dengan latar belakang dirinya sebagai warga Hungaria keturunan Yahudi, karena dalam sejarahnya Hungaria terus ditindas oleh Rusia yang mengobarkan Pan-Slavisme, apalagi baik di masa Kekaisaran Rusia ataupun di masa komunisme Soviet, penganiayaan dan penindasan orang Rusia terhadap kaum Yahudi terus berlanjut tanpa henti. Mungkin juga karena alasan inilah, Teller dan Oppenheimer pada akhirnya berpisah, dan pada saat dengar pendapat Oppenheimer, ia telah memberikan kesaksian yang tidak menguntungkan bagi Oppenheimer, dan dipandang sebagai pengkhianat di dalam kalangan dunia ilmu fisika. Namun di dalam buku ini, deskripsi tentang Teller relatif positif.
Dalam ilmu fisika konvensional fisikawan dibedakan menjadi dua kategori yaitu fisikawan teoritis dan fisikawan eksperimental, fisikawan teoritis biasanya juga ahli matematika yang sangat hebat, mahir menjelaskan dunia fisika yang rumit dengan pemikiran teoritis dan rumus matematika, sementara fisikawan eksperimental mahir menggunakan keahlian kedua tangan yang terampil, pemikiran yang inovatif, ketekunan dan konsentrasi yang cermat serta semangat selalu mempertanyakan, melakukan pembuktian, uji coba, bahkan menemukan dunia fisika. Dalam sejarah perkembangan akademis fisika, satu hal yang sangat aneh adalah: Biasanya seorang fisikawan teoritis juga adalah seorang fisikawan eksperimental yang sangat kacau, dan fisikawan teoritis yang semakin unggul maka akan semakin buruk pula dalam melakukan eksperimen, yang acap kali menimbulkan bencana kecil di dalam laboratorium.
Begitu pula dengan Oppenheimer dalam film “Oppenheimer”, di usia mudanya ia mengalami pukulan yang sangat hebat di laboratorium Cavendish yang terkenal di University of Cambridge di Inggris, bahkan mengalami depresi sehingga terjadilah insiden apel beracun; ia menyuntikkan zat beracun ke dalam sebuah apel, lalu apel itu diletakkannya di atas meja dosen pembimbingnya (seorang fisikawan eksperimental). Ini adalah kejadian nyata, kemudian melalui pengaruh keluarga Oppenheimer peristiwa tersebut baru dapat diselesaikan, tetapi salah satu syaratnya adalah Oppenheimer harus menjalani konseling psikologis selama periode tertentu. Sementara dalam film ini ada alur cerita dimana bapak mekanika kuantum yakni Niels Bohr, seorang warga negara Denmark nyaris memakan apel beracun, itu murni tergolong cerita fiktif.
Cerita yang sama, etnis Tionghoa pertama yang meraih hadiah Nobel fisika yakni Yang Zhen-Ning juga tipikal seorang fisikawan teoritis, saat menempuh studi dengan gelar doktor di University of Chicago juga pernah berusaha berhubungan dengan eksperimen fisika, alhasil tentu saja juga tidak begitu berhasil.
Dalam autobiografinya yang berjudul “Sekolah dan Mengajar 40 Tahun” Yang Chen-Ning menyebutkan, di antara sesama teman kuliah di University of Chicago akan selalu saling mengingatkan bahwa dimana ada Yang Chen-Ning disitu akan terjadi ledakan, dan ketika melakukan ekperimen sebaiknya menjauh darinya. Di tengah keputusasaan akibat kegagalan di laboratorium, Teller-lah yang dengan niat baik telah menasihatinya, agar ia menggunakan bagian teori yang telah dirampungkan untuk dapat menyelesaikan tesis gelar doktornya dengan baik.
Setelah lulus, Yang Chen-Ning mendapat perhatian Oppenheimer, dan datang untuk bekerja di Institute of Advanced Study Princeton, disinilah dimulai kerjasama fisika teoritis bersama dengan Lee Tsung-Dao, akhirnya keduanya berhasil meraih hadiah Nobel fisika.
Penulis lupa pernah membaca di buku apa, dikatakan Oppenheimer pernah mengucapkan kata-kata, yang makna garis besarnya adalah masa-masa dirinya merasa paling bahagia dan puas selama di Princeton adalah melihat Yang Chen-Ning dan Lee Tsung-Dao berjalan bersama di lapangan rumput Princeton sembari membahas tentang fisika teoritis. Mengingat kembali memburuknya hubungan Yang Chen-Ning dan Lee Tsung-Dao, lalu membandingkan lagi film “Oppenheimer” dengan dunia nyata, patut disesali akan banyaknya benci dan dendam antara para ahli fisika, yang di tengah keruwetan hubungan antar manusia, otak yang paling cerdas sekalipun, di tengah bidang akademis yang paling murni sekalipun, juga demikian rumit.
Setelah menyelesaikan gelar doktor di Northwestern University, sejak Agustus 1994 saya mulai menjadi peneliti pasca doktoral di Cornell University di Negara Bagian New York, AS; walaupun gelar akademis saya adalah teknik mesin dengan spesialisasi ilmu mekanik, tapi pasca doktoral saya justru di Engineering and Applied Physics di Cornell University, dan gedungnya bersebelahan dengan gedung jurusan ilmu fisika. Itu adalah jurusan fisika yang telah meraih begitu banyak hadiah Nobel, itu sebabnya setiap kali lewat di depan gedung jurusan ilmu fisika, saya selalu diselimuti perasaan penasaran dan rasa hormat.
Cornell University terletak di bukit yang sangat hijau, Finger Lakes yang diwarisi sejak zaman es dengan barisan pegunungan yang tinggi rendah, sehingga menciptakan pemandangan yang unik dan indah:
Berbagai gedung di kampus tersebar tinggi dan rendah di berbagai lokasi berbeda di perbukitan tersebut, dan salah satu landmark yang terkenal di kampus, adalah hamparan rumput di lahan miring yang hijau di depan gedung jurusan ilmu fisika, pada saat turun salju di musim dingin diselimuti hamparan salju putih yang tebal, di saat musim semi tiba akan berubah menjadi padang rumput yang sangat ijo royo royo; oleh sebab itu, mahasiswa-mahasiswa yang bahagia akan bermain ski di musim dingin, dan bermain seluncur rumput di musim panas, mereka bermain dengan riang gembira di lereng bukit itu.
Tempat kerja penulis terletak di atas bukit tersebut, sementara kantin favorit saya terletak di kaki bukit, oleh sebab itu setiap siang saya selalu berjalan menyusuri jalan setapak menuruni bukit melewati padang rumput yang luas itu dengan riang gembira, demi menikmati makan siang favorit ala masakan Chinese.
Setelah makan siang saya pergi ke Oline Library yang berada di sebelah kantin, mampir membaca buku-buku berbahasa Mandarin yang bernuansa klasik, lalu setelah puas baru kembali dengan perlahan menaiki lereng bukit itu balik ke gedung jurusan; mengenang kembali hari-hari itu, sungguh sepenggal kehidupan yang sangat menyenangkan dan sederhana.
Setiap siang hari menyusuri jalan menuruni bukit menuju kantin, saya acap kali bertemu seorang tua yang terlihat berusia sekitar 80 tahun, walaupun terlihat cukup tua, tapi tubuhnya masih cukup kuat, ia sering mengenakan jaket berwarna abu muda dan celana panjang yang longgar, sepasang sepatu kulit tua yang besar, dengan santai berjalan ke arah kantin. Wajahnya penuh dengan kerutan, memiliki hidung yang jelas besar, juga kening yang sangat tinggi, kepala penuh uban itu disisir ke belakang berkibar terkena tiupan angin dari danau.
Ekspresinya senantiasa nampak sangat berbahagia, dan setiap kali saya melewatinya di jalan setapak itu, selalu menoleh dan menyapanya “Hai”, dan ia juga selalu membalas dengan “Hai” beserta senyum lebar sambil melambaikan tangan kanannya. Sebenarnya ini hanyalah kesopanan mendasar yang sangat lumrah di AS,dan tidak ada yang istimewa.
Akan tetapi, setiap kali setelah menyapanya, selalu merasa seperti mengenal orang tua ini, tapi tidak bisa mengingat dimana pernah bertemu dengannya, hingga suatu hari karena ada keperluan tertentu saya masuk ke gedung jurusan ilmu fisika, di lorong gedung itu saya melihat foto-foto para peraih hadiah Nobel terdahulu di dinding lorong, saya baru tersadarkan bahwa orang tua itu ternyata adalah Hans Bethe yang terkenal itu, ia adalah master fisika teoritis yang meraih hadiah Nobel fisika. Ia awalnya orang Jerman, dilahirkan di Jerman dan setelah meraih gelar doktor, hanya karena di pihak ibunya ada garis keturunan campuran Yahudi, menyebabkan ia juga tidak diberi tempat di NAZI Jerman, akhirnya pada 1935 ia meninggalkan Jerman dan diterima di jurusan ilmu fisika Cornell University, setelah itu berkat pengusulan teori reaksi nuklir di dalam matahari dan perhitungan matematikanya ia meraih hadiah Nobel.
Sebelumnya di saat membaca buku Dyson, sudah mengetahui saat Dyson studi di Cornell University pada 1947, ia menjadi pengikut Hans Bethe untuk melakukan riset pasca doktoralnya, dan selalu memuji Hans. Sementara Feynman juga karena alasan Hans Bethe, kemudian mengikutinya di Cornell University setelah PD-II. Pada buku Feynman saya sering melihat foto Hans Bethe di masa muda, walaupun mungkin telah terpaut tiga sampai empat dekade, tapi saya masih bisa mengenalinya.
Mendapati hal-hal semacam ini tidak lantas mengubah rutinitas dalam kehidupan saya, setiap kali makan siang jika dari kejauhan melihatnya berjalan di depan, saya akan berusaha melewatinya lalu berpaling dan menyapanya; ia juga selalu membalas dengan senyum lebar, melambaikan tangan sambil menyapa, rambut di kepalanya semerawut karena terpaan angin. Entah mengapa, setiap kali setelah menyapanya di dalam hati saya selalu merasa sangat tabah, mungkin karena menyadari di kampus ini terdapat seorang master kelas berat seperti dirinya, hal inilah yang membuat hati saya merasa sangat tenang.
Penulis mencari di Google, Profesor Bethe meninggal dunia pada 2005, tutup usia pada 99 tahun, kurang dari 10 tahun setelah penulis meninggalkan Cornell University. Mengenangnya kembali, sebenarnya ini hanyalah hal remeh temeh yang tidak perlu ditulis secara khusus, tapi saya merasa hal kecil seperti inilah yang memperlihatkan sentuhan manusiawi dalam tradisi di kalangan akademisi AS dan Eropa, para tokoh yang disebut master itu walaupun memiliki kemampuan pikiran yang melebihi orang rata-rata, tapi sebenarnya sangat mudah dekat dengan siapa saja; menengok kembali sejumlah “master” di dalam negeri, begitu memperoleh gelar tertentu saja, acap kali akan dikerumuni oleh akademisi muda maupun para mahasiswa, dan dipuja-puja ibarat rembulan yang diusung ke langit, agak menyerupai drama televisi Jepang “Shiroi Kyoto”, ketika direktur rumah sakit yang berwibawa berkeliling, di belakangnya sekelompok dokter berjubah putih selalu mengiringinya. Setiap kali menyaksikan pemandangan itu, penulis selalu teringat akan pengalaman di padang rumput di lereng bukit Cornell University, teringat akan Hans Bethe yang berjalan perlahan seorang diri, dengan ekspresinya yang ramah dan bersahabat pada siapapun.
Munculnya Hans Bethe dalam film “Oppenheimer” juga tidak sedikit, karena dalam Proyek Manhattan ia menjabat sebagai ketua tim ilmu fisika teoritis, yang bertanggung jawab mengkalkulasi Critical To Quality (CTQ) elemen radioaktif, dan di kemudian hari dalam proses pemerintah AS berusaha menindas Oppenheimer, beberapa kali ia tampil mendukung sahabatnya Oppenheimer, ia adalah seorang akademisi top yang terhormat dan sangat disegani. Aktor yang memerankan Bethe dalam film itu cukup mirip dengan sosok aslinya, satu-satunya kekurangannya adalah aktor tersebut berperawakan terlalu tinggi, sehingga membuat penulis terheran-heran; saat menonton film itu di dalam hati penulis terus bergumam: Hans Bethe yang sebenarnya tidak begitu tinggi, karena penulis pernah melihatnya secara langsung! (sud/whs)